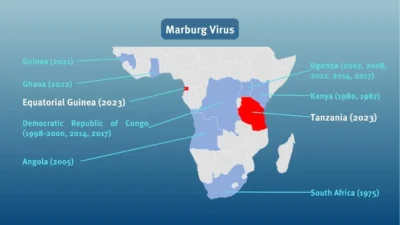Dunia dikejutkan dengan langkah berani sejumlah negara sekutu dekat Amerika Serikat. Inggris, Kanada, Australia, hingga Prancis dan beberapa negara Uni Eropa, secara mengejutkan kompak mengakui Negara Palestina.
Pengakuan ini terjadi menjelang sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan ini, di tengah agresi brutal Israel di Jalur Gaza yang terus memakan korban. Banyak pihak melihatnya sebagai bentuk penolakan terhadap agresi Israel yang didukung penuh AS.
Namun, ada satu faktor lain yang tak kalah menarik: keputusan ini muncul saat Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif impor tinggi yang bikin sekutunya meradang. Mungkinkah pengakuan Palestina ini jadi alat negosiasi ampuh melawan kebijakan Trump?
Mengapa Sekutu AS Berbalik Arah?
Langkah negara-negara yang selama ini dikenal sebagai "bestie" AS ini tentu bukan keputusan main-main. Mereka adalah kekuatan ekonomi dan politik penting di kancah global.
Pengakuan terhadap Palestina dianggap sebagai respons penting di tengah krisis kemanusiaan di Gaza. Solidaritas global terhadap Palestina yang terus menguat juga menjadi tekanan bagi pemerintah-pemerintah di Eropa dan negara sekutu AS lainnya.
Selama ini, Amerika Serikat dikenal sebagai pendukung setia Israel, terutama di bawah kepemimpinan Donald Trump yang punya hubungan kuat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keputusan sekutunya ini jelas menjadi tamparan keras bagi Washington.
Ketika Tarif Trump Bikin Sekutu Meradang
Di sisi lain, hubungan AS dengan sekutunya memang sedang diuji. Presiden Donald Trump dikenal dengan kebijakan ‘America First’ yang seringkali merugikan negara lain, termasuk para sahabatnya sendiri.
Trump telah menerapkan tarif impor yang bikin pusing kepala para pemimpin negara-negara tersebut. Kanada misalnya, dikenai tarif 35 persen, Inggris 25 persen, dan Australia 10 persen.
Prancis juga tak luput dari ‘hantaman’ tarif Trump sebesar 30 persen. Kebijakan ini jelas mengganggu stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional yang selama ini sudah terbangun.
Pemerintahan Inggris, misalnya, terus berusaha melobi untuk menurunkan tarif tersebut. Mereka bahkan sepakat untuk menurunkan tarif impor mobil dan produk dirgantara sebagai upaya negosiasi.
Pengakuan Palestina: Alat Negosiasi Ekonomi?
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menilai keputusan negara-negara Eropa itu mengambil langkah yang berlawanan dengan AS adalah perubahan cukup besar. Ini menunjukkan adanya pergeseran dinamika kekuatan global.
Yon Machmudi berpendapat bahwa secara politik, langkah ini bisa saja berkembang ke arah ekonomi. Terutama ketika Amerika Serikat dengan sewenang-wenang menetapkan tarif yang merugikan negara-negara Uni Eropa dan sekutunya.
"Dan mungkin saja peristiwa politik ini juga menjadi proses negosiasi di dalam masalah tarif yang sudah ditentukan Trump itu," ungkap Yon saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Senin (22/9).
Pengakuan terhadap Palestina ini bisa menjadi ‘kartu truf’ bagi sekutu AS untuk menekan Washington. Ini adalah sinyal bahwa mereka tidak akan lagi mengikuti setiap kebijakan AS secara membabi buta.
Bukan Murni Kemanusiaan, Ada Kepentingan di Baliknya
Yon Machmudi juga menegaskan bahwa pengakuan negara-negara ini tak murni karena alasan kemanusiaan atau peduli terhadap Palestina semata. Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional selalu menjadi prioritas utama.
"Jadi kita tidak bisa menemukan hanya murni serta merta kepedulian atau nilai-nilai kemanusiaan saja. Tentu lebih pada kepentingan: ada enggak kepentingan ekonomi di baliknya, ada enggak kepentingan politik domestik yang membuat mereka mengambil sikap itu," jelasnya.
Kepentingan tersebut bisa berupa politik domestik atau ekonomi. Misalnya, melemahnya dukungan politik untuk kepentingan kekuasaan di masing-masing negara bisa mendorong mereka mengambil sikap yang berbeda dari AS.
Gejolak Politik Domestik di Negara Sekutu
Beberapa negara yang mengakui Palestina memang sedang menghadapi gejolak politik domestik. Prancis, misalnya, dalam beberapa bulan terakhir mengalami pergantian perdana menteri berulang kali di bawah Presiden Emmanuel Macron.
Macron juga menghadapi gelombang demonstrasi yang memprotes kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, seperti pemangkasan layanan sosial dan penghematan anggaran. Seruan untuk mundur pun terus bergema.
Di Inggris, awal September lalu, Angela Rayner mundur dari posisi Wakil PM. Pemerintahan Inggris juga terguncang dengan demo anti-imigrasi yang terjadi belakangan ini.
Australia pun tak kalah panas. Pada awal September, warga dari berbagai kelompok menggelar unjuk rasa dengan tuntutan berbeda. Beberapa menggemakan dukungan Palestina, yang lain menyerukan anti-korupsi.
"Jadi kalau secara kemanusiaan atau dari sisi kepedulian untuk kondisi sekarang ini nampaknya sulit ditemukan, karena tidak ada. Apa yang menghubungkan solidaritas, apa yang menghubungkan negara Eropa dengan Palestina? Nah, ini perlu dilihat," ucap Yon.
Pemerintah negara-negara tersebut, kata Yon, memutuskan untuk mengakui Palestina karena pandangan rakyat Eropa yang menunjukkan solidaritas global terhadap Palestina. Ini adalah upaya untuk menyerap aspirasi publik.
Aspirasi Publik atau Strategi Politik?
Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Sya’roni Rofii, juga punya penilaian serupa. Dia menganggap pengakuan negara Eropa terhadap Palestina merupakan upaya menyerap aspirasi rakyat alih-alih atas inisiatif pemerintah sendiri.
"Saya melihat isu perdagangan tidak dalam kerangka dukungan Eropa terhadap Palestina. Para pemimpin Eropa cenderung mendengar aspirasi publik domestik yang mendukung Palestina," kata Sya’roni.
Meski begitu, Sya’roni mengakui hubungan Eropa-AS terutama di era Trump mengalami kemunduran. Bagi negara-negara di benua Biru, Negeri Paman Sam dianggap tak kooperatif dalam melindungi kepentingan mereka.
Masa Depan Aliansi AS-Eropa di Era Trump
Yon Machmudi menambahkan, pengakuan terhadap Palestina ini akan membuat AS dan negara Eropa menilai ulang aliansi yang sudah terbangun selama ini. Ini adalah momen krusial yang bisa mengubah peta politik global.
Kondisi tersebut juga akan membuat AS di bawah Trump mempertimbangkan kekuatan unilateralnya. Apakah Washington akan terus berjalan sendiri, atau kembali bekerja sama secara erat dengan sekutu-sekutunya?
Langkah berani para sekutu ini menunjukkan bahwa dunia tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan saja. Kepentingan nasional dan tekanan publik bisa menjadi faktor penentu dalam kebijakan luar negeri sebuah negara.
Pengakuan Palestina oleh sekutu dekat AS ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah sinyal kuat tentang pergeseran geopolitik, di mana isu kemanusiaan dan ekonomi saling berkelindan dalam sebuah tawar-menawar politik yang kompleks.